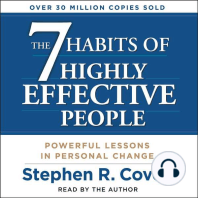Professional Documents
Culture Documents
An Kemiskinan Masih Sebatas Wacana
Uploaded by
Abu RizalOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
An Kemiskinan Masih Sebatas Wacana
Uploaded by
Abu RizalCopyright:
Available Formats
Pengentasan Kemiskinan Masih Sebatas Wacana
Ketika ditanya soal globalisasi, peraih Nobel, M Yunus, menjawab, "Masalah sebenarnya adalah globalisasi yang benar versus globalisasi yang salah. Jika kita berdiam diri membiarkan globalisasi mengalir tak terkendali, itulah globalisasi yang amat salah besar. Globalisasi semacam ini hanya didominasi perusahaan-perusahaan dan negaranegara berkekuatan besar. Mereka tidak akan memerhatikan kepentingan perusahaan atau negara-negara kecil." Apalagi jeritan kaum papa yang demi sembako murah atau uang receh harus berebut mempertaruhkan nyawa. Tak punya "grand strategy" Dalam kenyataannya, globalisasi yang salah kian mendominasi. Buktinya kesenjangan antara negara maju seperti G8 dan negara-negara Dunia Ketigaseperti Indonesiakian lebar. Di negara maju, warganya sudah membuat teknologi canggih, merancang hidup di luar angkasa. Di sini, kita masih berkubang dalam 1001 masalah, seperti rebutan tanah, listrik mati, narkoba, dan konflik sektarian. Keadaan kian runyam saat pergumulan politik di tingkat nasional terlalu banyak mengorbankan kepentingan bangsa dan menjurus rusaknya kohesi nasional. Sedikit saja kontraksi di level elite akan berdampak pada kekerasan kolektif atau tindakan anarkis. Akibat disibukkan 1001 persoalan, kita lupa tak mempunyai grand strategy menghadapi globalisasi. Karena itu, pemikiran dan aksi M Yunus, yang telah terbukti bisa memberdayakan orang miskin di negerinya, harus menjadi inspirasi untuk memberdayakan orang-orang miskin, agar mereka tidak semakin termarjinalkan. Ketamakan Dalam buku The Lugano Report:On Preserving Capitalism in Twenty-first Century (1999,2003), Susan George membeberkan ramalan mengenaskan pada tahun 2020. Saat itu sebanyak tiga miliar dari enam miliar penduduk dunia tidak masuk dalam perhitungan politik dan ekonomi; tidak ada tempat di permukiman kota dan di dalam ekologi. Kaum miskin juga rentan tergoda merusak lingkungan, seperti dilakukan 10 juta warga miskin kita yang mencari apa pun, termasuk membabat hutan demi mendapat makan. Untuk ini, mereka tak bisa dipersalahkan begitu saja. Jadi dalam beberapa kasus, kemiskinan punya andil bagi kerusakan hutan. Apalagi, harus diakui pemihakan bagi kaum miskin di negeri ini sering hanya berkutat pada wacana di tengah ambisi sebagian orang untuk meraup kekayaan secara tidak halal, entah uang suap atau parsel. Bahkan, dalam beberapa kasusbantuan tunai langsung atau Askeskinmereka yang kaya tega mengaku miskin demi mendapat jatah yang seharusnya diterima kaum miskin. Ketamakan orang berkecukupan itu mengingatkan kisah John G Wendel dan lima saudaranya yang dikenal sebagai orang-orang paling kaya di New York pada 1920-an. Meski mewarisi banyak kekayaan, hidup mereka amat
miskin dan tidak menikah. Mereka hidup dalam satu rumah yang sama selama 50 tahun. Saat satu-satunya perempuan dalam keluarga John meninggal pada 1931, aset kekayaannya diperkirakan 100 juta dollar AS. Yang mengejutkan, perempuan itu selama 25 tahun mengenakan gaun yang sama. Melawan kemiskinan Terkait kemiskinan, banyak pendapat dikemukakan. Kaum konservatif dengan tokoh Auguste Comte atau Emile Durkheim berpendapat, kemiskinan terjadi akibat kultur dan mentalitas orang miskin yang tidak bisa beradaptasi dengan tatanan sosial yang ada. Kaum konservatif selalu memandang positif struktur sosial yang ada. Karena itu, bagi kaum konservatif, kemiskinan bukan masalah serius. Di sisi lain, kaum liberal, dengan tokoh Fredrich August von Hayek (1889-1992), memandang kemiskinan sebagai masalah serius. Untuk mengatasinya, kaum liberal berpendapat, kultur orang-orang miskin harus diubah dengan pendidikan dan diskriminasi dieliminasi. Sayang, umumnya kaum liberal tidak mau mengubah struktur sosial yang sudah ada. Kebijakan Indonesia saat ini, misalnya, juga banyak disetir kaum neolib yang membuat kaum miskin kian terpojok. Lihat, mereka makin susah sekolah dan tak bisa dirawat di RS karena tak bisa membayar uang muka, tak dapat air bersih, tak dapat rumah, dan terpaksa tinggal di sembarang tempat. Sebagian lain banyak terkena gangguan jiwa (Kompas, 910/10/2007). Koalisi umat beragama Kita tidak boleh tinggal diam, dan harus bergerak melewati level wacana terkait pengentasan kemiskinan. Betapa hebatnya, jika makin banyak orang yang terketuk menyekolahkan anak-anak malang. Seluruh umat beragamaapa pun agamanyaharus berkoalisi mengatasi masalah ini. Coba simak ucapan mantan Presiden Tanzania Julius Nyerere, "Kalau sebagai umat beragama kita tidak aktif menentang struktur-struktur sosial dan organisasi-organisasi ekonomi yang menyebabkan orang menjadi miskin dan lapar, agama akan terdegradasi menjadi momok yang masih punya arti bagi para penakut. Jika agama dan umat beragama tidak mengungkapkan cinta kasih Allah dan tidak menjadi pionir dalam proses konstruktif terhadap keadaan manusia dewasa ini, agama justru akan disamakan dengan ketidakadilan dan penindasan."
Mana, "Jakarta Lebih Baik"?
Tatkala berkampanye sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta hampir tiga tahun silam, Fauzi Bowo selalu menyatakan akan membawa Ibu Kota ke posisi lebih baik. Kalimatnya, yang kemudian melekat di benak publik, adalah, Serahkan penanganan Ibu Kota kepada ahlinya.
Rasanya saya termasuk di antara warga Ibu Kota yang menanti dengan berdebar apa yang hendak dilakukan Fauzi Bowo ketika ia akhirnya dipercaya menjadi Gubernur DKI. Kota tua ini mempunyai segudang persoalan amat berat. Jakarta, misalnya, salah satu megapolitan di dunia yang lalu lintasnya sangat macet. Jakarta tidak memiliki angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) sebagaimana kita temukan di sejumlah kota Asia, seperti Beijing, Tokyo, Hongkong, dan Singapura. Jakarta pun tidak memiliki sky train sebagaimana Bangkok, Kuala Lumpur, dan Sydney. Jakarta memiliki busway, moda angkutan yang disukai warga, tetapi anehnya sampai sekarang terkesan belum digarap optimal. Jakarta, di sisi lain, mesti memiliki varian angkutan baru, yakni MRT, agar lalu lintas tidak semacet sekarang. Jakarta pun dianjurkan memiliki lebih banyak jalan layang dan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) sebagaimana misalnya diterapkan di Amerika Serikat dan Singapura. Ini baru mengenai urusan lalu lintas. Jakarta memiliki masalah pelik lain, yakni banjir yang sudah ada sejak era VOC. Banjir Kanal Barat sudah ada, tetapi dibutuhkan lagi Banjir Kanal Timur yang diharapkan menyerap banjir di kawasan timur Ibu Kota. Kota ini memiliki rakyat miskin amat besar, di atas 8 persen. Juga terjadi kesenjangan cukup lebar sebab di kota inilah bermukim kaum kaya dan terkaya di Tanah Air. Ancaman terhadap kecemburuan sosial tidak kecil. Identitas kota Di sisi lain, Jakarta belum memiliki identitas yang amat kuat, selain sebagai kota sangat macet. Mau disebut kota mode dan seni dunia, rasanya belum sampai di sana kelasnya. Kota bisnis kelas dunia? Masih jauh panggang dari api. Di Asia saja, Jakarta kalah dari kota-kota seperti Shanghai, Beijing, Tokyo, Osaka, Seoul, Mumbai, Hongkong, dan Singapura. Atau kota wisata? Idem dito, Jakarta kalah jauh dari Madrid, Wina, Paris, Beijing, Shanghai, Xian, Beirut, Dubai, Hongkong, bahkan Singapura. Lalu apa identitas kota ini, sebagaimana yang kita tahu lekat pada kota dunia lain seperti London, Paris, Singapura, Beijing, New York, Los Angeles, dan Mumbai? Dengan beragam masalah ini, tentu saja harapan besar banyak disandarkan pada bahu Fauzi Bowo. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu selama hampir tiga tahun ini ternyata harapan itu tinggal menjadi asa. Publik Jakarta sejauh ini belum merasakan gebrakan Fauzi Bowo, seorang planolog papan atas lulusan Jerman. Publik mengidamkan kota berpenduduk 10 juta jiwa ini lebih sejuk karena banyak pohon, polusi berkurang, dan kawasan pejalan kaki yang jauh lebih manusiawi. Ruang terbuka hijau di bawah 10 persen, padahal idealnya minimal 25 persen. Proyek warisan Hal menonjol yang dilakukan Fauzi adalah menuntaskan sejumlah proyek besar yang sudah dirintis para pendahulunya, yakni penyelesaian proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan penuntasan proyek Banjir Kanal Timur, yang membuat sebagian warga Ibu Kota tidak lagi disusahkan oleh banjir maut. Fauzi juga mampu membuat rakyat miskin bisa berobat gratis di pusat kesehatan masyarakat. Ini langkah yang patut dipuji. Akan tetapi, masyarakat berharap lebih dari sekadar penuntasan proyek lama tersebut. Publik ingin Fauzi Bowo membawa warga Jakarta lebih baik taraf hidupnya atau keluar dari wilayah kemiskinan karena Jakarta menjadi kota wisata utama dunia. Jakarta menjadi kota seni, kota musik, kota mode, atau kota belanja yang sangat progresif. Jakarta sebetulnya berpotensi besar sebagai kota belanja utama dunia karena memiliki banyak mal berkelas dan mal yang cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Harga barang-barang mewah di Ibu Kota tidak banyak berselisih dengan harga di New York, Chicago, London, Hongkong, dan Singapura.. Hakikatnya. Kita bisa dan mampu melakukannya. Masalahnya, terletak pada seberapa jauh kita kreatif, seberapa kuat kita membangun tim kerja yang paten, seperti apa kita melibatkan masyarakat untuk lebih dalam berpartisipasi untuk kotanya. Kalau beberapa aspek di atas bisa diwujudkan, Jakarta yang lebih baik akan tampak wujudnya. Apalagi kalau Gubernur mampu membuat terobosan. Misalnya, memelopori kafe bebas rokok di seluruh wilayah DKI. Selain itu, meningkatkan kriteria mengenai asap yang bisa dilepas oleh
kendaraan bermotor. Asap harus lebih bersih, dan karena itu harus menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Menanam pohon jauh lebih banyak dari yang ada sekarang. Kemudian, berjalan di depan dalam hal penggunaan energi. Misalnya, ia bisa mengeluarkan anggaran besar untuk menghasilkan energi matahari yang terbarukan, ramah lingkungan, dan sebagian listrik yang dihasilkan untuk rakyat miskin.
Bahasa Aceh Mulai Dianggap Bahasa Kampungan Oleh Sebagian Masyarakat Aceh
Bahasa mencirikan dan menandakan bangsa. Sepertinya sepotong kalimat ini tidak lagi bermakna bagi
sebagian masyarakat Aceh. Ciri utama sebagai sebuah bangsa/suku banyak dinomorsekiankan oleh masyarakat Aceh, merupakan sebuah realita lapangan yang dianggap bukan masalah oleh segelintir masyarakat Aceh yang sangat patut dipermasalahkan sebagai rasa tanggung jawab akan ke-Acehan bangsa ini, sebagai rasa tanggung jawab kita yang menyatakan diri bangsa/suku Aceh, juga sebagai rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh pribadi manusia walaupun itu lahir dari manusia, yaitu peninggalan paling berharga, peninggalan ciri bangsa dari nenek moyang (bahasa dan adat budaya Aceh). Jika ciri utama ditinggalkan, adat dan budaya sebagai ciri khas bangsa nomor dua tidak akan bisa dipertahankan apalagi dilestarikan. Bahasa tak ada bedanya dengan alur kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, bahasa lahir, hidup dan lenyap dengan masyarakat pemakainya (user). Kata lenyap, sungguh rangkaian enam huruf yang menjadi momok paling menakutkan bagi yang peduli dan bangga dengan bangsa, sebuah problema peradaban bangsa Aceh yang seharusnya dipikirkan berulang-ulang supaya di masa depan tidak menjadi peradaban Aceh yang tidak Aceh. Bahasa merupakan alat komunikasi turun temurun yang harus dipertahankan dan dilestarikan sebagai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan ciri khas bangsa sampai kiamat tiba. Hal ini sepertinya sudah dianggap masalah yang sepele, masalah yang dinomorurutkan di poin yang kesekian oleh sebagian masyarakat Aceh. Karena dewasa ini bahasa Aceh sepertinya menjadi bahasa nomor dua di Aceh sendiri setelah bahasa Indonesia, realita ini terjadi terutama di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan berlanjut ke daerah perkampungan dimana tempat letaknya ciri khas utama yang tinggi sebuah bangsa, dalam kontek ini; ciri khas bangsa Aceh. Dalam sebuah opini yang ditulis oleh Gerard Bibang, wartawan Ranesi, Gejala ini, ternyata, merupakan salah satu akibat dari apa yang disebut peperangan bahasa. Sekitar 6.000 bahasa besar di seluruh dunia terancam punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keanekaan bahasa sebagai bagian dari warisan keanekaan kebudayaan umat manusia, juga terancam punah. Bahasa Aceh kemungkinan besar masuk dalam kategori tersebut. Jika bahasa tidak bisa dipertahankan, adat yang lainnya akan sangat mudah lenyap mengikuti alur kemajuan penggunanya. Kemajuan yang sangat memundurkan. Bahasa Aceh merupakan bahasa regional (daerah) yang sangat rentan lenyap di masa depan. Bahasa nasional sendiri sekarang sangat banyak mengalami pencampuran dengan bahasa daerah (bukan tercampur dengan bahasa daerah Aceh), seperti kata saya dan kamu dalam percakapan sehari-hari banyak yang menggunakan kata gue dan lo (bahasa Betawi). Hilang standarisasi juga karena peperangan bahasa. Sepertinya suku Betawi menang dalam go on and survive ciri bangsa mereka. Di Indonesia, bahasa Aceh bahasa paling lemah, rentan lenyap ditikam bahasa nasional yang mulai hilang standarisasi tersebut dalam medan perang bahasa di Indonesia. Adat budaya Aceh sangat lemah dalam survive apalagi go on. Mulai dan bahkan sudah kalah dengan power adat budaya bangsa/suku lain. Tidak mampu menguasai medan perang karena pasukan Aceh sudah banyak yang tidak Aceh karena bahasa. Bahasa Aceh mulai kehabisan darah karena tikaman bahasa nasional, mulai lenyap. Tidak hanya bahasa, adat juga, mulai hilang di Aceh. Kreasi Aceh yang bernilai Aceh juga mulai ditikam dari dalam dan dari luar, salah satu contohnya lagu, lagu Aceh yang tidak bernilai Aceh, ditikam dari dalam, cuma meniru, contohnya, seperti lagu SMS, maaf, juga yang sedang ngepop sekarang di Aceh yaitu lagu intermezo dalam film Eumpang Breueh.
Bahasa. Utamanya bahasa, banyak bangsa ini yang tidak bisa bahasa bangsanya, apalagi menguasainya. Banyak yang malu menggunakan bahasa bangsa sebagai bentuk isyarat bahwa dia merupakan salah satu dari bangsa ini. Realita lapangan juga menunjukkan ada yang berpura-pura tidak bisa bahasa bangsa. Bahasa Aceh, bahasa geutanyoe telah banyak mengalami perubahan, dan mulai hilang karena rasa malu, rasa tidak PD menggunakan bahasa kampungan (bahasa Aceh), karena tidak bisa, karena tidak menguasainya sebab dari beberapa sebab oleh sebagian bangsa ini. Kata-kata perkata mulai hilang karena pengaruh dari sebab di atas, contohnya dari sekian banyak kata yang mulai hilang seperti kata camca (arti = sendok) sekarang sudah banyak yang langsung mengatakannya dalam bahasa Indonesia sendok dan boh limo juga terkena pengaruh bahasa Indonesia banyak yang langsung menyebutnya dengan boh jeruk . Pengaruh gaul tingkat tinggi. Juga dialek dan intonasi bahasa Aceh, banyak masyarakat Aceh sekarang yang menggunakan bahasa Aceh dalam intonasi rendah, seperti kata ureueng (orang) intonasinya lebih mendalam, banyak yang mengatakan dengan kata ureung yang intonasinya lebih dangkal, kata keubeue (kerbau) juga demikian, dsb . Kata-kata yang meugampong mulai ditinggalkan, banyak masyarakat yang tidak mengerti, seperti kata teumeugom, situek, poh cakra, dsb. Hanya sebagian masyarakat Aceh sekarang yang menggunakan kata, dialek dan intonasi bahasanya tanpa ada rasa malu dan rasa tidak PD tanpa sungkan-sungkan oleh mereka yang bangga dan peduli dengan ke-Acehannya dan oleh mereka yang karena pengaruh lingkungan tanpa didasari rasa bangga, tanpa didadasari oleh rasa tanggung jawab terhadap ciri khas bangsa ini. Ini persoalan besar yang sangat patut dipermasalahkan terhadap kelangsungan adat dan budaya Aceh, terhadap kekayaan bangsa akan keanekaan adat budaya yang ada di Indonesia yang merupakan aset daerah yang sangat dibanggakan terutama di luar negeri, dan dibanggakan di dalam negeri, tetapi tidak sangat karena juga banyak yang tidak bangga, contoh besarnya di Aceh. Budaya malu menggunakan bahasa sendiri juga mulai tumbuh dalam kehidupan sebagian masyarakat Aceh seiring dengan kemajuan jaman dan kemajuan pergaulan. Tanya kenapa? jawabannya diketahui oleh masyarakat Aceh sendiri. Dewasa ini banyak masyarakat Aceh tulen yang tidak bisa bahasa Aceh. Ini disebabkan banyak hal, terutama karena didikan orangtuanya. Anak-anak Aceh banyak yang diajarkan bahasa Indonesia oleh orangtuanya, orangtuanya yang malu dan tidak bangga dengan ke-Acehannya, orangtuanya yang tidak bisa bahasa Aceh karena neneknya, dst. Banyak masyarakat Aceh menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam keluarganya terutama di daerah perkotaan. Tapi sampai dewasa ada sebagian bahkan banyak anak yang tidak juga bisa bahasa Aceh, juga dikarenakan beberapa masalah, ada yang tidak mau belajar bahasanya nenek moyang dari lingkungannya sendiri karena ada anggapan bahasa Aceh cuma bahasa kampung, bahasa percakapan orang-orang kampung, di kota tidak berlaku, bahkan ada yang dengan bangga mengatakan aku nggak bisa bahasa Aceh demi pergaulan hebat, pergaulan tingkat atas anak-anak kota. Ada juga karena lingkungan yang memang dalam semua hal interaksi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia, walaupun sesama Aceh. Hal ini menyebabkan bahasa Aceh bukan lagi menjadi bahasa ibu oleh sebagian masyarakat Aceh. Kita takutkan beberapa keturunan ke depan akan ada yang menganggap bahasa bangsa Aceh adalah bahasa Indonesia. Aneh. Budaya paling aneh juga mulai tumbuh, yaitu; bisa bahasa Aceh, tapi pura-pura tidak bisa, malu menggunakannya. Berbicara meukeulido (intonasi rendah/bahasa celat) menjadi tren sebagian masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari (Maaf , permasalahan ini terutama didominir oleh kaum cewek, tidak ada maksud menjelekkan kebiasaan kaum perempuan, tapi begitulah kenyataannya). Banyak masyarakat Aceh yang padahal berasal kampung malah kadang-kadang berasal kampung terpencil hijrah ke kota pura-pura tidak bisa bahasa Aceh, berbicara menggunakan bahasa Aceh seolah-olah tidak bisa bahasa Aceh (meukeulido). Entah apa yang akan mereka dapatkan dengan ngomong meukeulido (celat, seolah-olah baru belajar bahasa tsb). Jika muncul pertanyaan terus apa yang bisa didapatkan dari ngomong bahasa Aceh? Jawabannya paling tidak kita menjadi pasukan yang gigih dan gagah dalam medan perang bahasa yang sebutkan di atas tadi. Bagi yang memang tidak bisa bahasa Aceh, mungkin agak bisa ditolerir oleh pihak yang peduli terhadap adat dan budaya Aceh, tapi ada orang tulen tinggalnya tepi pantai atau di pinggir gunung dan bisa berbahasa Aceh tulen, hijrah ke kota peugah haba meukeulido sang aneuk Jakarta bar teuka u Aceh (berbicara dengan bahasa celat seolah-olah anak Jakarta yang baru datang ke Aceh)
menjadi pasukan yang lari dari medan perang di mata mereka. Sudah banyak masyarakat Aceh yang tidak bangga menjadi suku Aceh. Bahasa Aceh mulai pudar, di lingkungan masyarakat dan lingkungan pemerintahan.Di Aceh ini dalam rapat adat sekalipun, pidato, diskusi banyak mengunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Aceh sendiri. Entah karena malu, atau mungkin bahasa Aceh dianggap bahasa tidak gaul oleh sebagian masyarakat Aceh. Malah kadang-kadang komunikasi hari-hari dengan sesama Aceh ada bahkan banyak yang menggunakan bahasa Indonesia (malu menggunakan bahasa sendiri). Apalagi dalam acara-acara yang menyangkut masalah pemerintahan, entah tujuannya supaya menjadi masyarakat yang nasionalis atau memang karena malu menggunakan bahasa Aceh karena dianggap bahasa norak (kampungan). Sebenarnya jika ada rasa ingin menjadi nasionalis dengan cara seperti itu justru tidak akan berjiwa nasional, sebab tidak melestarikan apa yang dibanggakan nasional itu sendiri, yaitu keanekaan adat budaya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Kepunahan bahasa adalah juga kepunahan sejarah peradaban. Jika satu kaum berhenti menggunakan suatu bahasa, maka kaum tersebut kehilangan beberapa kemampuan natural dari bahasa mereka. Jika bahasa Aceh lenyap, maka satu babak sejarah Aceh juga akan hilang. Mungkin permasalahan ini juga karena pengaruh global, tetapi pribadi masyarakat Aceh lain dari yang lain dewasa ini. Suku lain, seperti Padang, mereka juga termasuk provinsi/kota besar, banyak suku lain juga ada di sana, tetapi bahasa mereka tetap nomor satu, hampir tak ada yang mengaku Padang tidak bisa bahasa Padang. Misalnya suku lain datang ke sana dan mereka tahu bahwa orang tsb tidak bisa bahasa Padang, tetapi tetap mereka tegur pertama dengan bahasa mereka, dan jika kita menetap di satu daerah mereka, paling seminggu atau dua minggu mereka layani kita dengan bahasa Indonesia, mau tidak mau harus mempelajari bahasa mereka jika menetap di lingkungan mereka. Kemungkinan besar mereka juga akan menang dalam peperangan ini. Permasalahan ini merupakan tanggung jawab suatu bangsa (dalam kontek ini; bangsa Aceh) yang masih hidup sekarang kepada nenek moyang yang sudah berpulang. Memang menggunakan bahasa apapun adalah hak pribadi seseorang, tapi bahasa merupakan ciri khas bangsa/suku. Mencintai negara/bangsa/suku adalah bagian dari iman, melestarikan adat dan budaya adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap negara/bangsa/suku. Sebagai warga negara, seharusnya tidak hanya memiliki jiwa nasionalis, tetapi juga harus mempunyai jiwa regionalis dalam konteks ini, artinya tetap menjaga dan melestarikan adat budaya regional sendiri di samping juga melestarikan adat budaya nasional. Bayangkan jika sebuah bangsa tidak punya bahasa tetap, memakai bahasa orang sebagai alat komunikasi sesama, sungguh tidak mempunyai jati diri sebagai bangsa. Permasalahan adat dan budaya, yang mestinya dibudayakan oleh bangsa ini, bukan hanya oleh budayawan yang membudayakannya karena gaji. Permasalahan ini solusinya tergantung kepada pribadi masing-masing, semoga kita semua sebagai masyarakat Aceh bangga dengan ke-Acehan kita.
You might also like
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20027)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (3813)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12948)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5795)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3279)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionFrom EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (9756)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionFrom EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (728)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasFrom EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasRating: 4 out of 5 stars4/5 (9929)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)From EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9054)