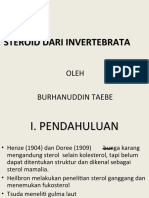Professional Documents
Culture Documents
Agonis Dan Antagonis Opioid
Uploaded by
Nita AndriyaniCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Agonis Dan Antagonis Opioid
Uploaded by
Nita AndriyaniCopyright:
Available Formats
AGONIS DAN ANTAGONIS OPIOID
Kata opium berasal dari bahasa Yunani yang berarti jus; jus yang berasal dari bunga opium merupakan sumber dari 20 jenis alkaloid opium.Opiate merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan obat-obatan yang berasal dari opium. Morphine berhasil diisolasi pada tahun 1803, lalu diikuti oleh codeine pada tahun 1832 dan papaverine pada tahun 1884. Morphine dapat disintesis secara buatan namun jauh lebih mudah bila diisolasi dari opium. Istilah narcotic berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah stupor dan sejak lama telah digunakan untuk menyatakan analgesik yang memiliki sifat seperti morphine. Pengembangan obat-obatan sintetis yang memiliki sifat seperti morphine semakin mempopulerkan penggunaan istilah opioid untuk menyatakan semua jenis substansi eksogen, yang bersifat alami maupun sintetik, yang dapat membentuk ikatan dengan reseptor opioid dan menghasilkan suatu efek agonis (yang menyerupai sifat morphine). Opioid dapat menghasilkan kondisi analgesia tanpa menghilangkan sensasi sentuhan, proprioseptif, maupun kesadaran. Klasifikasi yang biasa digunakan untuk opioid antara lain: agonis opioid, agonis-antagonis opioid, dan antagonis opioid. HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR DAN AKTIVITAS Alkaloid opium dapat dibagi menjadi dia kelas yakni: phenanthrene dan benzylisoquinolone. Alkaloid phenantrene yang dapat ditemukan pada opium antara lain morphine, codeine, dan thebaine. Alkaloid benzylisoquinolone yang ada pada opium, yang merupakan jenis alkaloid dengan aktivitas opioid yang lemah, antara lain papaverine dan noscapine. Tiga buah cincin inti phenanthrene terdiri dari 14 buah atom karbon. Cincin piperidine keempat terdiri dari sebuah nitrogen amine tersier dan rangkaian seperti ini sering ditemukan pada kebanyakan senyawa agonis opioid. Pada pH 7,4, nitrogen amine tersier akan terionisasi, sehingga lebih mudah larut dalam air. Ada keterkaitan antara struktur sterokimia opioid dengan potensinya, di mana isomer levorotary merupakan opioid yang paling aktif.
Opioid Semisintetik Opioid semisintetik berasal dari molekul morphine yang kemudian dimodifikasi secara relatif sederhana. Sebagai contoh, substitusi sebuah gugus methyl dengan sebuah gugus hydroxyl pada karbon 3 dapat menghasilkan senyawa methylmorphine (codeine). Penggantian gugus asetyl pada karbon 3 dan 6 akan menghasilkan
senyawa diacetylmorphine (heroin). Thebaine memiliki aktivitas analgesik yang tidak signifikan namun senyawa ini merupakan prekursor untuk senyawa etorphine (potensi analgesiknya > 1000 kali lipat dari morphine).
Opioid Sintetik Opioid sintetik mengandung inti phenanthrene dari morphine namun inti tersebut disintesis dengan menggunakan alat, tidak berasal dari modifikasi morphine. Derivat morphine (levorphanol), derivat methadone, derivat benzomorphan (petazocaine), dan derivat phenylpiperidine (meperidine, fentanyl) merupakan contoh kelompok snyawa opioid sintetik. Ada kemiripan antara berat molekul (236 hingga 326) dan pK derivat phenylpiperidine dengan anestetik lokal amide. Fentanyl, sulfentanyl, alfentanil, dan remifentanil merupakan jenis opioid semisintetik yang sering digunakan dalam anestesia umum pada pembedahan jantung. Ada perbedaan farmakokinetika dan farmakodinamika di antara semua obatobatan tersebut. Perbedaan utama tersebut terletak pada potensi dan laju ekuilibrasi antara plasma dan efek obat (biophase).
Mekanisme Aksi Opioid bertindak sebagai suatu agonis pada sterotipik reseptor opioid di neuron presinaptik dan postsinaptik sistem saraf pusat/SSP (terutama di batang otak dan sumsum tulang belakang/spinal cord) serta di luar SSP pada jaringan periferal. Kondisi hiperalgesik inflamasi kemungkinan besar berkaitan erat dengan aksi opioid antinociceptive. Mekanisme aksi periferal ini kemungkinan besar diaktivasi pada neuron aferen primer. Normalnya, reseptor opioid yang samaakan diaktivasi oleh tiga buah ligan reseptor peptida endogen yang dikenal sebagai enkephalins, endorphins, dan dynorphins. Ketiga ligan endogen ini memiliki aksi yang menyerupai opioid dengan cara berikatan dengan reseptor opioid sehingga dapat menimbulkan aktivasi sistem modulasi nyeri (antinociceptive). Adanya opioid dalam bentuk terionisasi sangat penting dalam proses pengikatan dengan reseptor anionik. Hanya opioid bentuk levorotary yang dapat menunjukkan aktivitas opioid. Oleh karena itu, secara alami, morphine juga berbentuk isomer levorotary. Tingkat afinitas kebanyakan agonis opioid berhubungan erat dengan potensi analgesiknya. Efek utama aktivasi reseptor opioid adalah menurunkan neurotransmisi. Penurunan neurotrasnmisi ini dapat terjadi karena adanya penghambatan pelepasan neurotransmiter presinaptik (acetylcholine, dopamine, norepinephrine, substance P), dan terkadang juga terjadi penghambatan bangkitan aktivitas di post-synaptic. Peristiwa biokimiawi yang diinisiasi oleh terikatnya reseptor opioid oleh agonis opioid ditandai oleh peningkatan konduktansi kalium (yang menyebabkan hiperpolarisasi), inaktivasi saluran kalsium, atau kombinasi kedua hal tersebut. Proses tersebut akan menyebabkan penurunan tiba-tiba pada pelepasan neurotransmiter. Inhibisi adenyl cyclase yang dimediasi oleh reseptor opioid tidak berperan dalam efek cepat opioid, namun kemungkinan besar mekanisme ini berperan dalam efek lambat melalui penurunan respon gen neuropeptidea cyclic adenosine monophosphate (cAMP) dan penurunan konsentrasi neuropeptida messenger (pembawa pesan) RNA/m-RNA. Reseptor opioid terletak pada ujung perifer neuron aferen primer dan aktivasi pada reseptor ini akan menyebabkan penurunan neurotransmisi atau penghambatan proses pelepasan neurotransmisi eksitasi, seperti substance P. Dengan pertimbangan ini, maka morphine yang diinjeksi secara intraartikuler (3 mg) dapat memberikan efek analgesia yang lebih lama meskipun prosedur artoskopi lutut sudah selesai dilakukan. Depresi transmisi kolinergik pada SSP yang diakibatkan oleh inhibisi pelepasan acetyl-choline dari ujung saraf memainkan peranan penting dalam menimbulkan efek
analgesia dan beberapa efek samping dari obat-obatan agonis opioid. Opioid tidak mempengaruhi tingkat respon pada ujung saraf aferen terhadap stimulasi noxious. Opioid juga tidak mengganggu konduksi impuls saraf di sepanjang saraf perifer. RESEPTOR OPIOID Reseptor opioid diklasifikasikan menjadi tiga buah reseptor yakni mu, delta, dan kappa. Reseptor opioid ini berasal dari gugus senyawa reseptor berpasangan guanine (G), dan senyawa ini dapat ditemukan pada 80% reseptor yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk untuk reseptor muskarinik, adrenergik, gamma-butyric acid, dan somatostatin. Sebuah gen reseptor-mu sudah berhasil diidentifikasi dan enam buah reseptor mu juga telah berhasil diketaui. Kemungkinan besar reseptor dari morphine-6-glucoronide merupakan varian dari reseptor mu. Sebuah agonis opioid yang ideal harus memiliki spesifitas yang tinggi terhadap reseptor, sehingga dapat menghasilkan respon yang diinginkan (analgesia) tanpa harus menimbulkan banyak efek samping (hipoventilasi, mual, muntah, ketergantungan fisik). Ketiga kelompok utama reseptor opioid juga berpasangan dengan protein G sehingga dapat ikut menghambat adenyl cyclase,menurunkan konduktansi gerbangvoltase saluran kalsium, atau membuka aliran masuk dari saluran kalium. Tiap proses tersebut dapat mengakibatkan penurunan aktivitas neuronal. Reseptor opioid juga memodulasi siklus hantaran sinyal phosphoinisitide dan phospholipase C. Hambatan pada aliran masuk kalsium dapat menyebabkan supresi pelepasan neurotransmiter (substance P) pada kebanyakan sistem neuronal. Hiperpolarisasi yang diakibatkan oleh adanya aksi di saluran kalium dapat mencegah eksitasi atau propagasi potensi aksi. Reseptor opioid dapat meregulasi fungsi dari sakuran ion lain termasuk aliran eksitasi post-synaptic yang dibangkitkan oleh reseptor N-methyl-D-aspartate (NMDA). Reseptor mu atau reseptor morphine berperan dalam tindakan analgesia supraspinal dan spinal. Aktivasi subpopulasi reseptor mu (mu1) dianggap berperan dalam menghasilkan analgesia, sedangkan reseptor mu2, berperan dalam menimbulkan hipoventilasi, bradikardia, dan ketergantungan. Meskipun begitu, cloning (penggandaan) reseptor mu tidak dapat mendukung keberadaan subtipe reseptor mu1 dan mu2. Kemungkinan besar timbulnya subtipe tersebut diakibatkan oleh modifikasi post-translasi protein. Endomorphins merupakan peptida dengan afinitas yang tinggi dan sangat selektif terhadap reseptor mu yang ada pada otak. Agonis reseptor mu eksogen antara lain adalah morphine, meperidine, fentanyl, sufentanil, alfentanil, dan remifentanil. Naloxone merupakan antagonis reseptor mu, zat ini dapat melekat pada reseptor mu namun tidak mengaktifkannya.
Agonis, termasuk ligan endogen dynorphin, dapat beraksi pada reseptor kappa, sehingga mengakibatkan inhibisi pelepasan neurotransmiter melalui saluran kalsium N. Depresi pernapasan yang diakibatkan oleh aktivasi reseptor mu, jarang ditemukan pada aktivasi reseptor kappa meskipun dysphoria dan diuresis biasanya menyertai aktivasi reseptor ini. Agonis-antagonis opiod biasanya mempengaruhi reseptor kappa. Reseptor delta dapat memberikan respon terhadap ligan endogen yang dikenal sebagai enkephalins, dan resepotr opioid ini berperan dalam memodulasi aktivitas reseptor mu. Sistem Supresi Nyeri Secara Endogen Peranan dari reseptor opiod dan endorphins jelas terlihat pada sistem supresi nyeri secara endogen. Reseptor opioid yang terletak pada otak (substantia griseus batang otak periaqueductal, amygdala, corpus striatum, hypothalamus) dan spinal cord (substantia gelatinosa) berperan dalam menimbulkan persepsi nyeri, integrasi impuls nyeri, dan respon terhadap nyeri. Diperkirakan bahwa endorphins dapat menghambat pelepasan neurotransmiter eksitasi dari ujung saraf yang menmbawa impuls nociceptive. Sehingga neuron akan ter-hiperpolarisasi, dan menekan pelepasan respon bangkitan yang dapat menimbulkan nyeri. Alangesia yang diinduksi oleh stimulasi listrik dari otak atau stimulasi mekanik dari area perifer (akupuntur) kemungkinan besar dapat melepaskan endorphins. OPIOID NEURAXIAL Penempatan opioid pada ruangan epidural atau subaraknoid dalam mengatasi nyeri akut atau kronik didasari oleh pengetahuan mengenai adanya reseptor opioid (terutama reseptor mu) pada substantia gelatinosa sumsum tulang belakang (spinal cord). Analgesia yang ditmbulkan oleh opioid neuraxial, berbeda dengan opioid yang diberikan secara intavena atau anestesia lokal yang diberikan secara regional. Karena opioid neuraxial tidak berhubungan dengan denervasi sistem saraf simpatetik, kelemahan otot rangka, ataupun hilangnya sensasi proprioseptif. Analgesia ini berkaitan erat dengan jumlah dosis (dosis epidural sekitar 5 hingga 10 kali dosis subaraknoid) dan opioid ini tidak terlalu bekerja pada nyeri somatik, namun spesifik pada nyeri visceral. Namun bila dibandingkan dengan rute neuraxial, opiod larut lemak seperti morphine dapat menghasilkan analgesia onset lambat namun durasi kerjanya jauh lebih lama jika diberikan secara intravena.
Farmakokinetika Opioid yang dimasukan pada ruangan epidural dapat diserap masuk ke dalam lemak epidural, absorpsi sistemik, atau difusi melalui dura ke dalam cairan serebrospinalis (CSF). Penetrasi obat melalui dura sangat dipengaruhi oleh tingkat kelarutan dalam lemak/lipid. Selain itu, berat molekul juga berperan dalam proses penetrasi ini. Konsentrasi fentanyl yang diberikan secara epidural dapat mencapai puncaknya sekitar 20 menit, sedangkan sulfentanil sekitar 6 menit. Sedangkan morphine butuh waktu sekitar 1 hingga 4 jam untuk bisa mencapai konsentrasi puncak di CSF. Efek Samping Efek samping opioid neuraxial terjadi karena adanya obat yang memasuki CSF atau sirkulasi sistemik. Secara umum, timbulnya efek samping sangat dipengaruhi oleh jumlah dosis opioid yang diberikan. Beberapa efek samping lainnya dipengaruhi oleh reseptor dan interaksi obat. Ada empat buah efek samping klasik dari opioid neuraxial yakni gatal/pruritus, mual dan muntah, retensi urin, dan depresi ventilasi. Pruritus/Gatal Pruritus merupakan efek samping yang sering ditemukan pada pemberian opioid neuraxal. Dan biasanya gejala ini terlokalisasi pada wajah, leher, atau dada bagian atas. Pruritus lebih sering terjadi pada pasien obstetrik, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya interaksi antara reseptor opioid dengan estrogen. Antagonis opioid seperti naloxone sangat efektif dalam mengtasi gatal yang diakibatkan oleh opioid. Secara paradoksal, antihistamine juga dapat mengatasi pruritus, namun efek sekundernya adalah dapat menimbulkan sedasi. Retensi Urin Jika dibandingkan dengan pemberian IV dan IM, maka insidensi retensi urin lebih sering ditemukan pada pasien muda yang mendapat opioid neuraxial. Retensi urin kemungkinan besar terjadi karena interaksi opioid dengan reseptor opioid di spinal cord bagian sacral. Interaksi ini dapat menghambat aliran sistem saraf parasimpatik sehingga menimbulkan relaksasi otot detrusor dan peningkatan kapasita buli-buli yang mengakibatkan retensi urin. Morphine epidural dapat menyebabkan retensi urin dalam 15 menit dan hal tersebut dapat bertahan selama 16 jam. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan naloxone. Depresi Ventilasi Efek samping serius dari opioid neuraxial adalah depresi ventilasi, yang dapat terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam setelah pemberian opioid. Banyak
yang melaporkan bahwa depresi ventilasi terjadi pada 1% populasi, dan kebanyakan disebabkan oleh pemberian fentanyl atau sulfentanil. Depresi ini terjadi karena absorpsi opioid ke dalam sirkulasi sistemik. Depresi pernapasan karena injeksi morphine intrathecal jarang terjadi. Faktor-faktor yang dapat menghambat timbulnya depresi pernapasan antara lain adalah jumlah dosis opioid yang digunakan dan penggunaan opioid kombinasi. Batuk dapat mempengaruhi pergerakan CSF sehingga semakin memperbesar kemungkinan depresi ventilasi. Pasien obstetrik kemungkinan besar tidak terlalu mengalami depresi ventilasi karena adanya stimulasi ventilasi dari progesterone. Sulit untuk mendeteksi depresi pernapasan pada pemberian opiod neuraxial karena terkadang laju napas tetap normal meskipun telah terjadi hipoksemia arterial dan hiperkarbia. Pulse oximetry dapat dijadikan salah satu alat untuk mendeteksi hal tersebut. Pemberian oksigen suplemental (2 liter/menit) merupakan terapi yang efetif untuk mengatasi hal tersebut. Infus naloxone profilaksis (0,25 g/kg/jam IV) cukup efektif dalam mengurangi terjadinya depresi pernapasan dan beberaapa efek samping lainnya. Sedasi Sedasi merupakan salah satu efek samping yang dapat ditemukan dari pemberian berbagai jenis opioid neuraxial, namun efek ini lebih sering ditemukan pada pemberian sulfentanil. Dan efek tersebut berhubungan erat dengan jumlah dosis opioid yang digunakan. Eksitasi Sistem Saraf Pusat Rigiditas otot rangka yang menyerupai aktivitas kejang tonik dapat timbul karena pemberian opioid IV dalam jumlah besar. Namun efek samping seperti ini jarang ditemukan pada opioid neuraxial. Miklonik justru lebih sering ditemukan pada opioid neuraxial, dan bahkan ada yang melaporkan mengenai efek samping berupa kejang grand mal. Migrasi opiod cephalad melalui CSF serta interaksi antara opioid dengan reseptor nonopioid di batang otak atau basal ganglia dianggap sebagai mekanisme yang berperan dalam eksitasi SSP oleh opioid. Dalam hal ini, opioid dapat menghambat inhibisi yang dimediasi oleh glycine atau gamma-aminobutyric acid. Reaktivasi Virus Ada laporan mengenai reaktivasi herpes simpleks labialis pada pasien obstetrik yang mendapat morphine epidural. Reaktivasi ini terjadi dalam 2 hingga 5 hari setelah pemberian opioid. Dan gejalanya lebih sering mengenai daerah yang
dipersarafi oleh saraf trigeminal. Mekanisme yang berperan dalam reaktivasi ini kemungkinan besar melibatkan migrasi cephalad opioid dalam CSF sehingga opioid tersebut dapat berinterkasi dengan nukelus trigeminal. Morbiditas Neonatal Absorpsi opioid secara sistemik akibat anestesia epidural dapat menyebabkan peningkatan kadar obat dalam serum darah neonatus. Sehingga hal ini dapat menyebabkan depresi ventilasi pada bayi baru lahir.
Efek Samping Lain Morphine epidural berhubungan juga dengan perpanjangan masa ereksi dan ketidakmampuan para pria dalam melakukan ejakulasi. Gejala-gejala seperti miosis, nistagmus, dan vertigo juga dapat ditemukan pada pasien yang mendapat opioid neraxial. Opioid neuraxial juga dapat menghambat pengosongan lambung. Penghambatan rasa gemetar oleh opioid neuraxial dapat menurunkan temperatur tubuh. Oligouria dan retensi urin yang bisa menyebabkan edema kemungkinan besar disebabkan oleh pelepasan vasopressin yang distimulasi oleh migrasi opioid neuraxial dalam CSF. Opiod neuraxial yang tercampur dengan bahan-bahan pengawet juga dapat menimbulkan kerusakan spinal cord dengan manifestasi klinis berupa disfungsi sensoris dan motoris, paresis, dan spasme mioklonik.
OPIOID AGONIST/AGONIS OPIOD Agonis opiod terdiri atas morphine, meperidine, fentanyl, sulfentanil, alfentanil, dan remifentanil. Namun agonis opioid tidak saja terbatas obat-obatan di atas. Masih ada beberapa jenis lain dari agonis opioid. Morphine Morphine merupakan prototip dari agonis opioid dan menjadi zat pembanding untuk semua jenis opioid lainnya. Pada manusia, morphine dapat menimbulkan alangesia, euphoria, sedasi, dan penurunan kemampuan konsentrasi. Sensasi lain yang dapat ditimbulkan oleh morphine antara lain mual, rasa hangat, rasa tebal pada ekstermitas, mulut kering, dan gatal, terutama pada daerah sekitar hidung. Morphine dapat menurunkan ambang batas nyeri dan memodifikasi persepsi yang berasal dari stimulasi noxious sehingga rasa nyeri yang timbul tidak akan lagi dianggap sebagai suatu perasaan nyeri. Rasa nyeri yang tumpul lebih mudah diatasi oleh morphine. Berbeda dengan analgesik non-opioid, morphine lebih efektif dalam mengatasi nyeri
visceral dan sensai nyeri yang berasal dari otot rangka, sendi, dan usus. Efek analgesia morphine akan lebih dominan apabila zat ini diberikan sebelum terjadi stimulus nyeri. Pada kondisi tanpa adanya stimulus nyeri, morphine bukannya menimbulkan euforia, justru lebih sering menyebabkan disforia. Farmakokinetika Morphine dapat diserap dengan baik melalui pemberian intramuskuler, dengan onset efek sekitar 15 hingga 30 menit dan efek puncaknya tercapai dalam 45 hingga 90 menit. Durasi kerja morphine dapat bertahan selama 4 jam. Morphine, 5 mg dalam 4,5 ml larutan salin dan dihirup sebagai aerosol dari nebulizer, dapat bekerja pada jaras saraf di jalan napas sehingga bisa mengatasi dispnea yang berhubungan dengan kanker paru-paru dan efusi pleura. Konsentrasi plasma morphine setelah injeksi intravena tidak berhubungan langsung dengan aktivitas farmakologis opioid. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan morphine dalam melakukan penetrasi ke sawar darah otak. Analgesia moderat membutuhkan konsentrasi plasma morphine sekurang-kuranya 0,05 g/ml. Diperkirakan bahwa < 0,1% morphine yang memasuki SSP ketika konsentrasinya dalam plasma telah mencapai puncak. Rendahnya penetrasi morphine ke SSP antara lain disebabkan oleh (a) rendahnya kelarutan relatif morphine ke dalam lemak, (b) tingginya ionisasi morphine dalam pH fisiologis, (c) ikatan protein, (d) terjadi konjugasi yang cepat dengan asam glucoronic. Alkalinisasi darah, seperti yang dihasilkan oleh hiperventilasi paru-paru, akan meningkatkan fraksi morphine yang tak terionisasi sehingga akan memudahkan morphine ketika memasuki SSP. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aliran darah yang diinduksi oleh karbon dioksida lebih berperan dalam menghantarkan morphine ke otak. Tidak seperti fentanyl, morphine tidak mengalami uptake first pass ke dalam paru-paru.
Metabolisme Jalur utama metabolisme morphine adalah konjugasi dengan asam glucoronic pada hati dan lokasi ekstra-hati, terutama di ginjal. Sekitar 75% hingga 85% dosis morphien akan berbentuk morphine-3-glucoronide, dan 5% hingga 10% akan berbentuk morphine-6-glucoronide. Secara farmakologis, morphine-3-glucoronide bersifat tidak aktif, sedangkan morphine-6-glucoronide dapat menimbulkan analgesia dan depresi ventilasi melalui aksi agonis pada reseptor mu.
Metabolisme ginjal memegang kontribusi yang besar dalam metabolisme morphine. Hal ini menjelaskan mengapa pada pasien sirosis hati, masih dapat terjadi proses pembersihan morphine. Faktanya, metabolisme ginjal akan semakin meningkat seiring dengan adanya gangguan metabolisme hati. Eliminasi morphine akan terganggu pada pasien yang mengalami gangguan ginjal sehingga dapat menimbulkan akumulasi opioid yang dapat mengakibatkan depresi ventilasi. Pembentukan konjugasi glucoronide dapat terganggu oleh inhibitor monoamine oxidase (MAO) . Hal ini menjelaskan adanya penambahan efek morphine ketika diberikan bersama obat-obatan inhibitor MAO.
Waktu Paruh Eliminasi Eliminasi morphine-3-glucoronide jauh lebih lama dari eliminasi morphine itu sendiri. Morphine akan mengalami eliminasi karena metabolisme, dan hanya sedikit konsentrasi morphine yang dikeluarkan melalui urin dalam bentuk utuh. Pasien yang mengalami gagal ginjal akan menunjukkan peningkatan konsentrasi morphine dan metabolitnya dalam plasma dan CSF. Sehingga kita harus berhati-hati apabila hendak memberikan morphine pada orang yang mengalami gagal ginjal.
Jenis Kelamin Jenis kelamin dapat mempengaruhi analgesia opioid namun besarnya efek tersebut tergantung pada banyak variabel, termasuk jenis opioid yang digunakan. Jika dibandingkan dengan pria, maka morphine menunjukkan potensi analgesik dan kecepatan offset yang lebih lambat pada wanita. Morphine tidak mempengaruhi ambang batas apneik wanita, namun hal tersebut dapat meningkatkan ambang batas apneik pria. Sensitivitas hipoksik juga dapat mengalami penurunan pada wanita, namun hal itu tidak terjadi pada pria. Efek Samping Sistem Kardiovaskuler Pemberian morphine, meskipun dalam dosis besar (1 mg/kg IV), pada pasien supine dan normovolemik tidak akan menyebabkan depresi miokardial secara langsung atau hipotensi. Namun jika pasien tersebut diubah posisinya menjadi posisi berdiri, maka hal tersebut dapat menyebabkan hipotensi ortostatik dan syncope. Hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena gangguan respon kompensasi dari sistem
saraf simpatetik. Efek lain dari gangguan respon simpatetik ini dapat menyebabkan gangguan aliran balik vena sehingga menurunkan curah jantung dan tekanan darah. Morphine juga dapat menyebabkan penurunan tekanan darah sistemik yang disebabkan oleh bradikardia atau pelepasan histamine. Pemberian opioid (morphine) sebagai medikasi preoperatif atau sebelum induksi anestesia (fentanyl) cenderung dapat menyebabkan penurunan denyut jantung, terutama ketika terpapar dengan anestetik volatil. Premedikasi dengan menggunakan antihistamin H1 dan H2 tidak dapat mempengaruhi pelepasan histamine yang diakibatkan oleh morphine, namun tindakan ini dapat mencegah terjadinya perubahan tekanan darah sistemik dan resistensi pembuluh darah sistemik. Morphine tidak akan mensensitasi jantung terhadap katekolamin ataupun menyebabkan disaritmia jantung selama tidak ada hiperkarbia atau hipoksemia arterial yang bisa terjadi apabila ada depresi ventilasi akibat opioid. Takikardia dan hipotensi yang terjadi selama prosedur operasi bukan disebabkan oleh morphine, namun sebagai akibat dari respon tubuh terhadap stimulasi nyeri yang tidak berhasil disupresi oleh morphine. Respon kardiovaskuler dipengaruhi oleh sistem saraf simpatetik dan mekanisme renin-angiotensin. Kombinasi beberapa obat opioid dengan anestetik inhalan dapat menyebabkan hipontensi. Ventilasi Semua opioid dapat menimbulkan efek depresi ventilasi yang dipengaruhi oleh jumlah dosis dan jenis kelamin. Depresi ventilasi yang diinduksi oleh opioid memiliki ciri berupa penurunan respon pusat ventilasi terhadap karbon dioksida, yangi ditandai oleh peningkatan PaCO2 dan pergersaran kurvatura respon karbon dioksida ke arah kanan. Agonis opiod juga dapat mempengaruhi pusat pernapasan medullry yang berperan dalam regulasi ritme pernapasan. Efek depresi pernapasan dapat terjadi dengan sangat cepat dan bertahan hingga beberapa jam. Opiod dosis tinggi dapat menyebabkan apnea. Kematian akibat overdosis opiod paling sering disebabkan oleh depresi ventilasi. Opioid dapat menyebabkan depresi aktvitas ciliary di jalan napas. Peningkatan resistensi jalan napas setelah pemberian opioid mungkin disebabkan oleh efek langsung pada otot polos bronkial dan pelepasan histamine. Supresi Batuk Opioid dapat menekan batuk dengan cara mempengaruhi pusat napas medullary yang letaknya berbeda dengan pusat ventilasi. Supresi batuk secara
maksimal dapat dihasilkan oleh codeine. Supressi batuk juga dapat dihasilkan oleh isomer opioid dextrorotary (dextromehrophan) yang tidak menghasilkan efek analgesia.
Sistem Saraf Apabila opioid tidak menghasilkan hipoventilasi, maka obat ini dapat menyebabkan penurunan aliran darah serebral dan tekanan intrakranial (ICP). Opioid harus hati-hati digunakan pada pasien yang mengalami cedera kepala karena (a) pengaruh opioid berkaitan dengan kesadaran, (b) dapat menyebabkan miosis, (c) dapat menyebabkan depresi ventilasi yang berhubungan dengan peningkatan ICP jika PaCO2 meningkat. Cedera kepala juga dapat mengganggu integritas sawar darah otak sehingga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap opioid. Sedasi Titrasi morphine pascaoperasi dapat menginduksi sedasi yang mendahului onset analgesia. Rekomendasi yang biasa digunakan dalam titrasi morphine adalah membuat interval di antara tiap injeksi bolus (sekitar 5 hingga 7 menit) agar kita dapat menilai efek klinis dari opioid. Traktus Biliaris Opioid dapat menyebabkan spasme otot polos bilier yang mengakibatkan peningkatan tekanan intrabilier sehingga bisa menimbulkan distres epigastrik atau kolik bilier. Nyeri seperti ini dapat dikacaukan oleh angina pectoris. Naloxone dapat menghilangkan nyeri kolik seperti ini. Meskipun begitu, nyeri kolik tidak selalu terjadi pada semua pasien, insidensinya adalah sekitar 3% dari semua pasien yang mendapat suplemen fentanyl. Kontraksi otot polos duktus pankreatikus kemungkinan besar berperan dalam peningkatan kadar amilase dan lipase yang ditemukan setelah pemberian morphine. Hal ini sering salah didiagnosis sebagai pankreatitis akut. Traktus Gastrointestinal Beberapa opioid seperti morphine, meperidine, dan fentanyl, dapat menimbulkan efek spasme otot polos gastrointestinal, yang mengakibatkan beberapa efek samping seperti konstipasi, kolik bilier, dan keterlambatan pengosongan lambung. Morphine dapat menghambat kontraksi propulsi peristaltik pada usus halus dan usus besar serta memperkuat tonus spinchter pyloric, katup ileocecal, dan
spinchter anus. Oleh karena itu akibat efeknya tersebut, maka pada masa lalu morphine sering digunakan sebagai obat diare. Efek morphine pada traktus gastrointestinal dapat dibalikkan dengan menggunakan antagonis opioid. Mual dan Muntah Mual dan muntah yang diinduksi oleh opioid dapat terjadi karena adanya stimulasi langsung pada zona pemicu kemoreseptor (chemoreceptor trigger zone) di dasar ventrikel keempat. Hal ini menunjukkan bahwa agonis opioid dapat menjadi agonis dopamin parsial pada reseptor dopamine di zona pemicu kemoreseptor. Morphine juga dapat menyebabkan mual dan muntah dengan cara meningkatkan sekresi gastrointestinal dan menghambat pengosongan isi lambung. Sistem Genitourinarius Morphine dapat meningkatkan tonus dan aktivitas peristaltik ureter. Berbeda dengan efek pada otot polos traktus biliaris, efek opioid pada traktus urinarius dapat dibalikkan efeknya dengan menggunakan antikolinergik seperti atropine.
Perubahan Kutaneus Morphine dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah kutaneus. Hal tersebut mengakibatkan wajah, leher, dan dada bagian atas berwarna kemerahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pelepasan histamine. Pelepasan histamine yang terlokalisasi, terutama pada vena yang menjadi tempat injeksi morphine, bukanlah suatu reaksi alergi. Sering kali, pelepasan histamine secara lokal, hipotensi ortostatik, mual dan muntah salah diinterpretasi sebagai suatu reaksi radang. Plasenta Plasenta tidak dapat menjadi sawar yang ideal terhadap opioid. Oleh karena itu depresi neonatus dapat terjadi karena pemberian opioid pada ibu selama proses persalinan. Penggunaan opioid secara kronik dapat menyebabkan timbulnya gejala ketergantungan Interaksi Obat Efek depresi ventilasi dari beberapa opioid dapat diperbesar oleh amphetamine, phenothiazine, monoamine oxidase inhibitor, dan antidepresan trisiklik. Obat-obatan simpatomimetik dapat memperbesar efek analgesia dari opioid. pada neonatus. Pemberian naloxone pada neonatus dapat mempresipitasi sindrom putus obat yang dapat mengancam jiwa neonatus.
Sedangkan obat-obatan sistem kolinergik dapat menghambat efek analgesia dari opioid. Toleransi Farmakodinamika dan Ketergantungan Fisik Toleransi farmakodinamika dan ketergantungan yang terjadi akibat penggunaan opioid secara berulang-ulang merupakan salah satu karakteristik dan kelemahan utama yang dimiliki oleh semua jenis opioid. Toleransi silang antara opioid juga dapat terjadi. Toleransi merupakan suatu kondisi di mana terjadi penambahan dosis agonis opioid guna mencapai efek analgesik yang sebelumnya dapat dicapai dengan dosis yang lebih rendah. Toleransi seperti ini biasanya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Hipotesis pertama mengenai toleransi farmakodinamika berhubungan dengan perubahan neuroadaptif akibat penggunaan opioid dalam jangka panjang. Semua reseptor opioid menjadi terdesensitasi akibat penurunan transkripsi dan jumlah reseptor. Hipotesis kedua mengenai toleransi berkaitan dengan peningkatan regulasi sistem cyclic adenosine monophosphate (c-AMP). Paparan opioid dalam jangka panjang berkaitandengan penurunan jaras c-AMP secara bertahap. Pemanjangan masa paparan dapat mengaktivasi reseptor NMDA melalui mekanisme second messenger serta menurunkan transporter glutamate spinal. Hal ini menyebabkan toleransi opioid dan sensitivitas nyeri yang abnormal,
Perubahan Hormonal Morfin dapat menyebabkan penurunan progresif dari konsentrasi kortisol plasma. Efek utama opioid pada aksis hipotalamus-pituitari-gonad melibatkan pengaturan pelepasan hormone termasuk peningkatan prolactin dan penurunan lutenizing hormone (LH), follicle stimulating hormone(FSH), testosteron, dan konsentrasi estrogen. Perubahan imun Terapi neuroendokrin opioid atau bisa efek menyebabkan langsung pada perubahan sistem imunitas imun. melalui efek Opioid mengubah
perkembangan, diferensiasi, dan fungsi dari sel imun akibat pengaruhnya pada reseptor opioid pada sel imun. Overdosis Prinsip dari overdosis opioid adalah depresi pernafasan hingga dapat menyebabkan apneu. Triasnya berupa miosis, hipoventilasi dan koma. Penanganannya dengan ventilasi mekanik dengan oksigen dan pemberian antagonis opioid misalnya naloxone. Morphine-6-Glucuronide Waktu kerja morphine-6-glucuronide lebih lama, efek analgesiknya juga 650x lebih kuat dari morfin oleh karena afinitasnya yang lebih tinggi terhadap reseptor opioid. Namun, akumulasi morphine-6-glucuronide selain berefek analgesik juga dapat mendepresi pernapasan.Morphine-6-glucuronide tidak akan menimbulkan efek klinis atau analgesik apabila diberikan dengan dosis bolus IV tunggal atau bolus IV diikuti dengan infus selama 4 jam. Hal ini menunjukkan rendahnya permeabilitas sawar darah otak terhadap morphine-6-glucuronide dan jangka pendek tidak cukup menekankan bahwa pemberian infus menghasilkan konsentrasi
optimal morphine-6-glucuronide pada SSP agar berefek farmakologis. Farmakokinetika Meperidine memiliki potensi 1/10 morfin dengan dosis 80-100 mg IM setara dengan 10 mg morfin. Durasi kerja 2-4 jam dan memberi efek sedasi, euphoria, nausea, vomitus, dan depresi napas seperti morfin, namun dapat diserap baik pada traktus gastrointestinal. Metabolisme Metabolisme hepatik meperidine sangat luas oleh karena 90% dari obat langsung mengalami demetilasi menjadi normeperidine dan dihidrolisis menjadi asam
meperidinik. Dieksresi melalui urin dan bergantung pada pH. Normeperidine dapat dideteksi dalam urin hingga 3 hari setelah pemberian meperidine dan komponen ini dapat menstimulasi SSP. Toksisitasnya memberi gejala mioklonus, kejang, dan gangguan fungsi ginjal. Waktu Paruh Eliminasi Obat Waktu paruh eliminasi mepiridine adalah 3-5 jam karena klirensnya bergantung pada metaboisme hepatic. Waktu eliminasi tidak akan berubah dengan pemberian dosis meperidine hingga 5mg/kg/IV. Penggunaan Klinis Prinsip penggunaan meperidine adalah untuk analgesic selama proses melahirkan dan masa post-operatif. Obat ini dianggap paling baik untuk pemberian intratekal. Meperidine efektif untuk menekan kejadian menggigil post operasi karena kerjanya pada -2 reseptor yang mengkontribusi efek anti-shiverin, namun hal ini dapat menyebabkan perubahan pada peningkatakan konsumsi oksigen. Meperidine dapat diberikan peroral sehingga lebih baik dari morfin, namun tidak efektif pada terapi diare dan antitusif sehingga kurang berguna pada bronkoskopi. Meperidine tidak diberikan dalam dosis tinggi karena dapat memberi efek inotropik negative terhadap jantung dan pelepasan histamine pada sejumlah pasien. Efek samping Pada dosis terapeutik, obat ini dapat menyebabkan hipotensi ortostatik akibat intervensi efek refleks kompensasi sistem saraf simpatis. Berbeda dengan morfin, meperidine tidak menyebabkan bradikardi, tetapi menimbulkan takikardi. Pemberian dengan dosis yang lebih besar dapat menurunkan kontraktilitas miokard. Delirium dan kejang timbul apabila telah terjadi akumulasi obat ini. Sindrom serotonin (instabilitas autonom) dapat terjadi bila ada pemberian obat yang merangsang pelepasan serotonin atau pada pasien yang diberikan meperidine dengan kombinasi antidepresan (Monoamine oxidase inhibitors, fluoxetin) Opioid ini dapat melewati plasenta, namun efek konstipasi dan retensi urin lebih sedikit dari morfin. Miperidine cenderung menyebabkan midriasis, mulut kering, dan takikardi yang menunjukkan efek seperti atropin. Dapat terjadi gejala putus obat akibat penghentian pemberian meperidine, namun lebih cepat, durasinya singkat, dan efek sistem saraf otonomnya lebih sedikit daripada morfin. Fentanyl Sebagai analgesik, fentanyl memiliki efek 75-125x lebih poten daripada morfin.
Farmakokinetika Fentanyl dosis tunggal intravena memiliki onset yang lebih cepat dan durasi kerja yang lebih singkat dari morfin oleh karena sifat lipofilik dari fentanyl sehingga dapat melewati sawar darah otak dengan mudah. Sebaliknya, durasi singkat fentanyl disebabkan oleh redistribusi cepat pada jaringan-jaringan inaktif seperti lemak dan otot skelet. Paru merupakan salah satu tempat penyimpanan dengan estimasi 75% dari dosis awal fentanyl. Metabolisme Fentanyl dimetabolisme menghasilan norfentanyl, hydroxypropionyl fentanyl, dan hydroxypropionyl-norfentanyl. Norfentanyl disekresi oleh ginjal dan dapat ditemukan dalam urin selama 72 jam setelah pemberian dosis tunggal IV fentanyl. Waktu Paruh Eliminasi Obat Waktu paruuh eliminasi obat ini lebih lambat dibandingkan morfin sehingga volume distribusi obat lebih besar. Lebih dari 80% dari dosis yang disuntikkan sudah tidak berada dalam plasma < 5menit. Pemanjangan waktu pareuh eliminasi fentanyl pada pasien usia lanjut disebabkan oleh penurunan laju klirens opioid karena volume distribusi tidak berubah bila dibandingkan pada pasien yang lebih muda. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan aliran vena porta hepatic akibat usia, atau produksi albumin oleh karena fentanyl sebagian besar terikat protein (79-87%). Jadi jarang pemberian dosis fentanyl bisa lebih lama pada pasien usia lanjut. Context-Sensitive Half Time Durasi pemberian infus kontinyu fentanyl meningkat melebehi 2 jam dan context-sensitive half time pada opioid ini menjadi lebih besar dari sufentanil. Cardiopulmonary Bypass Semua opioid menunjukkan penurunan konsentrasi plasma pada awal cardiopulmonary bypass. Penurunannya lebih sedikit pada opioid yang memiliki volume distribusi yang besar. Penggunaan Klinis Secara klinis, fentanyl dapat diberikan dalam cakupan dosis yang cukup luas. Dosis rendah fentanyl 1-2 g/kg/IV diberikan untuk efek analgesia. Fentanyl 220 g/kg/IV diberikan sebagai tambahan untuk anestesi inhalasi guna mengurangi respons sirkulasi terhadap intubasi ETT atau perubahan mendadak akibat stimulasi operasi. Dosis besar fentanyl, 50-150 g/kg/IV dapat digunakan tunggal untuk anestesi operasi.
Fentanyl dapat diberikan transmukosal dengan dosis 5-20 g/kg dengan tujuan untuk mengurangi kecemasan dan memfasilitasi induksi anestesi, terutama pada anak-anak. Dosis fentanyl transmukosal bergantung pada usia dan penggunaannya. Usia 2-8 tahun, dapat diberikan 15-20 g/kg 45 menit sebelum induksi anestesi. Pada usia 6 tahun dengan pemberian fentanyl transmukosal per oral 15 g/kg dapat meningkatkan insidens vomitus. Untuk terapi postoperative setelah operasi ortopedi, 1 mg fentanyl oral transmukosal setara dengan 5mg morfin IV. Dapat diberikan fentanyl transdermal 75-100 g/jam dengan kadar mencapai puncak dalam waktu 18 jam dan stabil selama anestesi masih terpasang. Pemberian transdermal fentanyl dilakukan sebelum induksi anestesi dan ditinggalkan hingga24jam postoperasi.
Efek Samping Efek samping yang ditimbulkan akibat fentanyl seperti pada pemberian morfin. Depresi pernapasan rekuren atau persisten akibat fentanyl merupakan masalah penting yang sering terjadi setelah operasi. Efek Kardiovaskular Berbeda denngan morfin, meskipun diberikan dalam dosis yang besar, fentanyl tidak akan merangsang pelepasan histamine sehingga tidak akan terjadi dilatasi pembuluh dara venula yang mengakibatkan hipotensi. Namun demikian, kontrol perubahan tekanan darah perlu dilakukan pada pasien neonatus yang diberikan fentanyl oleh karena cardiac output-nya bergantung pada denyut jantung. Reaksi alergi jarang terjadi akibat pemberian obat ini. Aktivitas Kejang Kejang dapat timbul akibat pemberian cepat fentanyl, sufentanil, dan alfentanil intravena. Namun, setelah pemberian cepat fentanyl 150 g/kg/IV pada konsentrasi plasma setinggi 1750 ng/ml, tidak ditemukan bukti EEG yang menunjukkan adanya aktivitas kejang. Sebaliknya, pemberian opioid dapat menyebabkan mioklonus sekunder akibat depresi sel saraf inhibisi dengan gambaran klinis kejang tanpa adanya perubahan EEG. Rangsangan Potensial Somatosensoris dan Electroencephalogram Dosis fentanyl 30 g/kg/IV akan menyebabkan perubahan pada rangsangan potensial somatosensoris, namun demikian, meski dapat dideteksi, pemeriksaan dengan monitor EEG tidak dianjutkan selama proses anestesi.
Tekanan Intrakranial Pemberian fentanyl dan sufentanil pada pasien dengan trauma kepala berkaitan dengan sedikit peningkatan tekanan intracranial (6-9 mmHg) meskipun tidak ada perubahan rumatan PaCO2. Peningkatan ini diikuti dengan penurunan nilai rata-rata tekanan arterial (MABP) dan tekanan perfusi serebral (CPP). Interaksi Obat Konsentrasi analgesic dari fentanyl meningkatkan potensi efek midazolam dan menurunkan kebutuhan penggunaan propofol. Kombinasi opioid-benzodiazepine menunjukkan efek sinergis hypnosis dan depresi pernapasan. Sufentanil Sufentanil merupakan analog thienyl dari fenanyl. Potensi analgesik sufentanil adalah sekitar lima hingga sepuluh kali dari fentanyl. Hal itu disebabkan oleh sufentanil memiliki afinitas yang jauh lebih besar terhadap reseptor opioid jika dibandingkan dengan fenanyl. Farmakokinetika Waktu paruh eliminasi sufentanil berada di antara waktu paruh fentanyl dan alfentanil. Vd dan waktu paru eliminasi sulfentanil mengalami peningkatan pada pasien yang obesitas, karena obat ini sangat larut dalam lipid. Ikatan sufentanil terhadap protein jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan fentanyl. Sulfentanil memiliki fraksi bebas yang jauh lebih banyak pada neonatus. Hal itu yang menyebabkan sulfentanil dapat memberikan efek depresi ventilasi yang jauh lebih besar ketika berada dalam plasma neonatus. Metabolisme Sulfentanil dimetabolisme secara cepat oleh N-dealkylation pada nitrogen piperidine dan O-demethylation. Penggunaan Klinis Dosis tunggal sufentanil 0,1 hingga 0,4 g/kg IV dapat memberikan efek analgesia yang lebih baik dan depresi ventilasi yang jauh lebih sedikit dari efek yang dihasilkan oleh fentanyl pada dosis yang sama (1 hingga 4 g/kg IV). Meskipun dosis besar sufentanil (10 hingga 30 g/kg IV) dan fentanyl (50 hingga 150 g/kg IV) tidak memberikan banyak perubahan pada hemodinamika pasien sehat, namun perubahan hemodinamika tetap saja bisa terjadi karena adanya respon katekolamin terhadap stimulus bedah. Gangguan ventilasi bisa saja terjadi pada pemberian sufentanil yang diakibatkan oleh adanya rigiditas otot-otot pernapasan.
Alfentanil Alfentanil merupakan analog fentanyl yang tidak terlalu poten (potensinya seperlima hingga sepersepuluh) dan durasi kerjanya hanya sepertiga dari durasi kerja fentanyl. Farmakokinetika Alfentanil memiliki waktu paruh eliminasi yang singkat jika dibandingkan dengan fentanyl dan sufentanil. Sirosis hati dapat memperpanjang waktu paruh tersebut. Namun gangguan ginjal tidak mempengaruhi waktu paruh eliminasi alfentanil. Waktu paruh alfentanil pada anak-anak jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa Vd alfentanil pada anak jauh lebih kecil. Vd alfentanil sekitar empat hingga enam kali lebih kecil dari fentanyl. Sekitar enam kali lebih kecildari sulfentanil. Karena alfentanil memiliki kelarutan dalam lipid yang lebih rendah dan ikatannya terhadap protein jauh lebih besar. Pada neonatus, waktu paruh eliminasi alfentanil jauh lebih cepat. Metabolisme Alfentanil dimetabolisme melalui dua jalur independen yakni piperidine Ndealkylation menjadi noralfentanil, yang merupakan metabolit utama, dan amide Ndealkylation menjadi N-phenylproprionamide. Alfentanil lebih banyak dimetabolisme di hati oleh aktvitas P-450 (CYP3A). Perubahan pada aktivitas P-450, seperti penggunaan erythromycin, dapat mengganggu metabolisme alfentanil. Waktu Paruh Eliminasi Waktu paruh eliminasi alfentanil jauh lebih lama dari sufentanil, sekitar 8 jam. Penggunaan Klinis Alfentanil memiliki onset dan offset yang cepat. Karakteristik ini menyebabkan alfentanilm dapat digunakan untuk mengatasi stimulasi noxious akut, seperti yang terjadi pada intubasi trakeal. Sebagai contoh, pemberian alfentanil 15 g/kg IV selama 90 detik dapat membantu dalam menghambat respon tekanan darah dan denyut jantung. Alfentanil 150 hingga 300 g/kg IV yang diberikan secara cepat, , dapat menghilangkan kesadaran pasien selama 45 detik. Setelah induksi seperti ini, maintenance anestesia dapat dipertahankan dengan memberikan alfentanil continous, 25 hingga 50 g/kg/jam IV, yang dikombinasikan dengan anestetik inhalan.
Remifentanil Remifentanil merupakan agonis opioid yang selektif terhadap reseptor mu, dengan potensi analgesik yang sama dengan fentnayl (sekitar 15 hingga 20 kali lebih poten dari alfentanil) dan laju ekulibrasi-nya pada otak sama dengan alfentanil. Meskipun secara kimia menyerupai gugus fenanyl, namun struktur remifentanil lebih unik karena zat ini memiliki rantai ester. Hal ini menyebabkan remifentanil (a) memiliki aksi kerja yang cepat, (b) lebih mudah dititrasi karena onset dan offset-nya lebih cepat, (c) pasien lebih cepat siuman ketika pemberian dihentikan. Ventilasi Pemberian 0,5 g/kg IV remifentanil dapat menyebabkan penurunan respon ventilasi terhadap karbon dioksida. Namun efek ini dapat cepat pulih hanya dalam waktu 15 menit. Kombinasi propofol dan remifentanil dapat menghasilkan efek sinergistik yang dapat memperparah depresi ventilasi. Farmakokinetika Farmakokinetika remifentanil ditandai oleh Vd yang kecil, pembersihan yang cepat, dam variabilitas efeknya lebih sedikit jika dibandingkan dengan opioid lainnya. Karena memiliki waktu eliminasi yang cepat, maka remifentanil memiliki keunggulan farmakokinetika. Farmakokinetika remifentanil pada pasien obesitas tidak jauh berbeda dengan farmakokinetikanya pada orang normal. Waktu bersihan remifentanil sekitar delapan kali lebih cepat dari alfentanil. Metabolisme Remifentanil merupakan suatu opioid yang unik karena dapat dimetabolisme menjadi metabolit inaktif oleh esterase jaringan dan plasma yang non-spesifik. Metabolit utama remifentanil, asam remifentanil, sekitar 300 hingga 4.600 kali kurang poten jika dibandingkan dengan remifentanil, dan metabolit ini diekskresikan melalui ginjal. Selain itu, metabolisme remifentanil tidak dipengaruhi oleh gagal ginjal maupun gagal hati selama metabolisme esterase tidak terganggu. Waktu Paruh Eliminasi Sekitar 99,8% remifentanil dieliminasi pada fase distribusi (0,9 menit) dan fase waktu paruh eliminasi (6,3 menit). Penggunaan Klinis Remifentanil dapat digunakan secara klinis karena memiliki profil farmakokinetika yang unik. Pada kasus-kasus di mana kita menginginkan efek analgesia yang dalam untuk waktu singkat, maka kita bisa menggunakan
remifentanil. Remifentanil memiliki efek depresi ventilasi yang jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan opioid lainnya. Anestesia dapat diinduksi dengan menggunakan remifentanil, 1 g/kg/IV yang diberikan selama 60 hingga 90 detik, atau dengan inisiasi bertahap menggunakan infus 0,5 hingga 1,0 g/kg/IV selama 10 menit, sebelum memberikan agen hipnotik standar pada intubasi trakeal. Remifentanil, 0,05 hingga 0,1 g/kg/menit IV yang dikombinasikan dengan midazolam, 2 mg IV, dapat memberikan efek sedasi dan analgesia yang efektif pada pasien yang mendapat perawatan anestesia. Sebelum menghentikan penggunaan remifentanil, maka kita harus memberikan opioid yang memiliki masa kerjanya lebih panjang agar analgesia pasien dapat terjamin ketika pasien telah siuman. Penggunaan remifentanil secara spinal atau epidural tidak dianjurkan karena hingga saat ini tingkat keamanannya belum teruji. Remifentanil, 100 g IV, dapat menurunkan respon hemodinamik akut terhadap terapi elektrokonvulsif. Efek Samping Karena memiliki onset dan offset kerja yang singkat, maka begitu infus remifentanil terhenti, maka seketika itu pula efek kerjanya akan hilang. Semua keluarga fentanyl, termasuk remifentanil, memiliki efek samping berupa kejang. Efek samping lain yang dapat timbul adalah mual, muntah, dan penurunan tekanan darah yang tidak terlalu besar. Depresi pernapasan yang disebabkan oleh remifentanil tidak akan diperparah oleh disfungsi hati maupun ginjal. Remifentanil dosis besar dapat menurunkan aliran darah otak dan kebutuhan oksigen metabolik otak tanpa mengganggu reaktivitas otak terhadap karbon dioksida. Remifenanil dapat menghambat pengosongan kandung empedu, namun jangka waktunya lebih singkat dari efek opioid lainnya. Remifentanil dapat menembus plasenta, namun efeknya pada neonatal tidak terlihat. Toleransi Opioid Akut Dosis remifentanil post-operative biasanya lebih banyak dari dosis preoperative, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh adanya toleransi opioid akut. Namun tidak terlalu banyak data yang mendukung hal ini. Codeine Codeine terbentuk dari hasil substitusi sebuah gugus methyl pada gugus hydroxl di atom karbon 3 morphine. Adanya gugus methyl menyebabkan metabolisme hati first-pass mengalami hambatan sehingga codeine bisa diberikan secara oral. Eliminasi codeine secara oral atau IM adalah sekitar 3 hingga 3,5 jam.
Sekitar 10% codeine di-demetilasi di hati menjadi morphine, dan hal ini bisa menimbulkan efek analgesia. Sedangkan sisanya, codeine diubah menjadi norcodeine, yang kemudian dikonjugasi atau dieksresi melalui ginjal. Pada dosis 15mg, codeine merupakan antitusif yang efektif. Analgesia maksimal, yang dapat dihasilkan oleh pemberian aspirin 650 mg, dapat dihasilkan oleh codeine 60 mg. Ketika diberikan secara IM, codeine 120 mg memiliki efek yang sama dengan morphine 10 mg. Tramadol Tramadol analgesic yang bekerja sentral yang memiliki afinitas sedang terhadap reseptor mu dan afinitas lemah terhadap reseptor opioid kappa dan delta, namun lebih kurang potensial 5-10x dari morfin sebagai analgesik. Tramadol merupakan gabungan dua enantiomer dimana salah satunya berfungsi menghambat pengambilan pengambilan norepinefrin, kembali sedangkan yang satunya serta berfungsi menghambat Tramadol (reuptake) serotonin pelepasannya.
dimetabolisme oleh enzim hepatic p-450. Tramadol 3mg/kg secara oral, IM atau IV efektif untuk penanganan nyeri sedang hingga berat. Tramadol berguna dalam penanganan nyeri kronik karena tidak ada efek adiksi dan tidak menyebabkan toksisitas organ atau efek sedatif yang bermakna.Efek samping obat ini adalah interaksinya dengan antikoagulan Coumadin dan kejang yang dapat timbul (hindari penggunaan pada pasien epilepsy atau pasien yang sementara berobat anti-kejang atau antidepresan). Heroin Heroin adalah opioid sintetik yang dihasilkan oleh asetilasi dari morfin. Oleh karena sifatnya yang lipofilik, heroin mudah menembus sawar darah otak sehingga onsetnya lebih cepat. Selain itu, efek mual kurang namun lebih berpotensial menimbulkan ketergantungan fisik. AGONIS-ANTAGONIS OPIOID Agonis-Antagonis Opioig tidak hanya terbatas pada pentazocine, butorphanol, nalbuphine, buprenorphine, nalophrine,bremazocine, dan dezocine. Obat-obat ini berikatan pada reseptor mu dimana mereka akan membatasi respon tertentu. Keuntungan penggunaan agonis-antagonis opioid adalah kemampua untuk menimbulkan efek analgesia dengan mengurangi depresi pernapasan dan rendahnya potensial ketergantungan terhadap obat
Pentazocine Pentazocine merupakan derivate benzomorphan yang bekerja separti agonis opioid dengan efek antagonis lemah. Efek antagonis ini dapat mencetuskan terjadinya gejala putus obat apabila diberikan pada pasien yang telah mengkonsumsi opioid sehari-hari. Efek agonis pentazocine di-antagonis oleh naloxone. Farmakokinetika Pentazocine diabsopsi baik setelah pemberian oral maupun parenteral. Metabolisme jalur hepatic cukup besar dengan sisa obat daam sirkulasi tinggal 20% setelah pemberian oral. Penggunaan klinis Pentazocine 10-30 mg IV atau 50 mg per oral yang paling sering digunakan untuk menangani nyeri sedang. Pentazocine bagus untuk terapi nyeri kronik ketika terdapat resiko tingi ketergantungaan.
Efek Samping Efek samping yang paling umum adalah sedasi yang diikuti dengan diaphoresis dan pusing. Sedasi cenderung terjadi setelah pemberian pentazocine via epidural. Pemberian berlebihan dapat menimbulkan disforia termasuk timbulnya rasa takur mati. Akibat pelepasan katekolamin, dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, tekanan darrah, tekanan arteri pulmonaldan tekanan akhir diastolic ventrikel kiri. Butorphanol Butorphanol merupakan agonis-antagois opioid yang mewakili pentazocine, namun dengan efek agonis yang 20x lebih kuat dan efek antagonis yang 10-30x lebih kuat. Butorphanol dengan cepat dan hampir semua diabsorpsi setelah injeksi IM. Pada pasien postoperasi, dosis 2-3 mg IM menghasilkan efek analgesia dan depresi napas setara dengan 10 mg morfin. Efek samping Efek samping yang umum terjadi adalah sedasi, mual dan diaphoresis. Disforia jarang dilaporkan. Depresi nepas timbul seperti pada pemberian morfin. Gejala putus obat timbul setelah pemberhentian tiba-tiba setelah terapi lama dengan butorphanol, tetapi gejalanya lebih ringan. Nalbuphine Nalbuphine merupakan agonis-antagonis opioid yang berkaitan kimia dengan oxymorphone dan naloxone. Efek analgesiknya setara dengan morfin, dan dari potensi nalorphine sebagai antagonis. Nalbuphine dimetabolisme di hati dan waktu paruh eliminasinya 3-6 jam. Efek samping yang paling umum adalah sedasi dengan insidens disforia lebih jarang bila dibandingkan dengan pemberian pentazocine atau butorphanol. Pemberian obat ini tidak meningkatkan tekanan darah, tekanan arteri pulmonal, denyut jantung, atau tekanan pengisian atrium sehingga nalbuphine bagus diberikan pada pasien dengan penyakit jantung Efek antagonis nalbuphine pada reseptor mu berupa manfaat untuk menekan efek depresi pernapasan yang menetap akibat efek agonis opioid selama masa rumatan anestesi. Buprenorphine Buprenorphine adalah agonis-antagonis opioid yang berasal dari opium alkaloid thebaine. Efek analgesiknya sangat baik dimana 0,3 mg setara dengan 10mg morfin. Onsetnya 30 menit setelah pemberian IM dan durasinya kurang dari 8 jam. Diperkirakan afinitas buprenorphine terhadap reseptor mu 50x lebih kuat dari pada
morfin. Buprenorphine efektif untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperti pada saat operasi atau yang berkaitan dengan kanker, kolik ginjal, dan infark miokard. Efek Samping Efek samping yang dapat timbul mual,munta, cenderung mengantuk, dan depresi pernapasan yang hampir sama pada pemberian morfin tetapi dapat lebih lama atau resisten terhadap antagonis, yakni naloxone. Nalorphine Nalorphine sama potensinya sebagai analgesik dengan morfin tetapi tidak terlalu baik pada penggunaan klinis akibat insidens disforia yang tinggi oleh karena aktivitas obat ini pada reseptor sigma. Bremazocine Bremazocine merupakan derivate benzomorphan yang dua kali lebih poten disbanding morfin sebagai analgesic, dan pada hewan tidak menunjukkan adanya keterantungan fisik atau depresi pernafasan. Gagalnya naloxone memberikan efek reverse terhadap efek sedasi bremazocine merupakan bukti bahwa obat ini beraktivitas pada tempat lain selain di reseptor mu. Dezocine Dezocine, 0.15 g/kg/IM merupakan agonis-antagonis opioid yang potensi analgesic, onset dan durasi kerjanya sebanding dengan morfin. Absopsi obat ini 1015mg, setelah diberikan IM cepat dan lengkap dengan efek analgesia yang timbul setelah 30 menit. Setelah pemberian dezocine 5-10 mg, efek analgesic muncul 15 menit kemudian. Penambahan dosis yang diberikan tidak mempengaruhi perubahan pada tekanan darah, tekanan arteri pulmonal atau cadiac output. Dezocine memiliki afinitas kuat pada resetor mu dan afinitas sedang pada reseptor delta. Insidens disforia yang rendah menggambarkan afinitas obat ini kurang terhadap reseptor sigma. Meptazinol Meptazinol merupakan sebagian agonis opioid yang relatif selektif terhadap reseptor mu1. Hal ini menyebabkan, tidak terjadi depresi napas dengan pemberian meptazinol dosis analgesic (100mg IM setara 8mg morfin). Onsetnya cepat tetapi durasinya kurang 2 jam. Bioavabilitas setelah pemberian oral <10%. Efek samping berupa ual, muntah, kadang ditemukn miosis tanpa adanya konstipasi maupun efek ketergantungan fisik terhadap obat.
ANTAGONIS OPIOID Perubahan kecil pada struktur agonis opioid dapat mengkonversi obat menjadi antagonis opioid pada satu atau lebih reseptor opioid. Naloxone Naloxone merupakan antagonis nonseletif pada ketiga reseptor opioid. Durasi kerja naloxone yang singkat (30-45 manit) diperkirakan akibat eliminasinya yang cepat pada ota sehingga diperlukan pemberian infus kontinyu untuk mempertahankan efek antagonis. Dengan pemberian 5g/kg/jam dapat mencegah depresi napas tanpa mengubah efek analgesia oleh opioid neuroaksial. Naloxone terutama dimetabolisme di hati dan waktu paruh eliminasinya adalah 60-90 menit. Efek Samping Mual dan muntah timbul berkaitan dengan dosis dan kecepatan bolus obat. Insidens dapat dikurangi dengan pemberian pelan selama 2-3 menit. Pemberian naloxone juga dapat merangsang aktivvitas saraf simpatis yang dapat menyebabkan timbulnya gejala nyeri. Peran dalam Penanganan Syok Naloxone memperbaiki kontraktilitas miokard yang bergantung pada dosis obat dan menunjukkan kemampuan bertahan pada hewan dengan syok hipovolemik daripada syok septik. Naltrexone Berbeda dengan naloxone, obat ini sangat efektif dengan pemberian oral menghasilkan efek antagonis terhadap efek agonis opioid selama 24 jam. Nalmefene Nalmefene merupakan antagonis opioid murni yang merupakan analog 6methylene dari naltrexone. Dosis yang direkomendasikan adalah 15-25 g/IV setial 25 menit hingga efek yang diinginkan tercapai dengan dosis total tidak melewati 1 g/kg. Pemberian nalmefene sebagai profilaksis menurunkan kebutuhan pemberian antiemetic dan antiprurits pada pasien yang menggunakan morfin PCA (patient controlled analgesia). Durasi waktu kerjanya lebih lama karena laju klirens yang lambat bila dibandingkan dengan morfin. Dimetabolisme melalui proses konjugasi di hati, <5% diekskresi tanpa mengalami perubahan ke urin. Methylnaltrexone Methylnaltrexone lebih aktif pada reseptor opioid perifer daripada di sentral karena ketidakmampuannya menembus SSP. Obat ini mempengaruhi pengosongan lambung dan mengurangi insidens mual dan muntah.
You might also like
- Analgesik Opioid Dan AntagonisDocument10 pagesAnalgesik Opioid Dan AntagonisAdi NugrahaNo ratings yet
- Resep AntidepresanDocument14 pagesResep AntidepresanZaki Achmad NhrNo ratings yet
- Gagal JantungDocument7 pagesGagal Jantungapt. Abdul Rakan Jamaludin, S.Farm., C.Ht, CI, C.N.NLPNo ratings yet
- ThiopentalDocument5 pagesThiopentalSara WilliamsNo ratings yet
- Steroid Laut Tak Lazim TweenspanDocument84 pagesSteroid Laut Tak Lazim Tweenspantweenwithspan_7711No ratings yet
- Interaksi Prasugrel dan WarfarinDocument3 pagesInteraksi Prasugrel dan WarfarinStev GamingNo ratings yet
- Reseptor OpioidDocument3 pagesReseptor OpioidOchtavianus0% (1)
- Jawaban Pertanyaan Diskusi RadiofarmasiDocument8 pagesJawaban Pertanyaan Diskusi RadiofarmasiGeby OrlanceNo ratings yet
- BAB I EditDocument85 pagesBAB I EdityanairpianiNo ratings yet
- Neuro Stroke Hemoragik 23 Juni 2021Document80 pagesNeuro Stroke Hemoragik 23 Juni 2021WahyuniNo ratings yet
- KELOMPOK 3 - Uji Efek Obat Pada KardiovaskularDocument96 pagesKELOMPOK 3 - Uji Efek Obat Pada KardiovaskularRonaldo JemaduNo ratings yet
- Poliferasi sel dan siklus selDocument2 pagesPoliferasi sel dan siklus selAkun DiniNo ratings yet
- ACNE MakalahDocument13 pagesACNE MakalahUkhtidestiyusufNo ratings yet
- INTERAKSIDocument34 pagesINTERAKSIsukma wirdaningsihNo ratings yet
- Makalah PCD Kasus WasirDocument23 pagesMakalah PCD Kasus WasirrizkykiameliaNo ratings yet
- ASMADocument122 pagesASMAMelie AngNo ratings yet
- Definisi ReplikasiDocument8 pagesDefinisi ReplikasiTria YussantiNo ratings yet
- Metabolisme dan EndokrinDocument25 pagesMetabolisme dan Endokrinrendy kurniawanNo ratings yet
- CeftriaxoneDocument35 pagesCeftriaxonerieyu93No ratings yet
- 5 1169574377008660511Document14 pages5 1169574377008660511kertaNo ratings yet
- Agonis Selektif Reseptor β1, Beta 2, Alfa 1Document2 pagesAgonis Selektif Reseptor β1, Beta 2, Alfa 1Anin_200496No ratings yet
- Tugas SP IO - Chapter 31Document46 pagesTugas SP IO - Chapter 31Yus MiaNo ratings yet
- FITOFARMAKADocument42 pagesFITOFARMAKAMila Aditya ZeniNo ratings yet
- Mekanisme Kerja Dari IritasiDocument39 pagesMekanisme Kerja Dari IritasiDavid FernandoNo ratings yet
- Tatalaksana Ulkus PeptikumDocument13 pagesTatalaksana Ulkus PeptikumimesNo ratings yet
- FARINGITISDocument18 pagesFARINGITISTridelShop100% (1)
- Makalah Hipertensi EsensialDocument10 pagesMakalah Hipertensi EsensialeedputraNo ratings yet
- Algoritma Dan Penyelesaian KasusDocument7 pagesAlgoritma Dan Penyelesaian KasusMarsha Budi ClarasatiNo ratings yet
- Keracunan AlkoholDocument35 pagesKeracunan AlkoholakivaNo ratings yet
- Logbook Fts Semi Solid Dan LiquidDocument30 pagesLogbook Fts Semi Solid Dan Liquidmharimawan sanjayaNo ratings yet
- ANTIBIOTIKDocument11 pagesANTIBIOTIKSalwa RWNo ratings yet
- Farmakologi Sso NewDocument53 pagesFarmakologi Sso NewGINo ratings yet
- JUDULDocument13 pagesJUDULSepti Andrianti AzhariNo ratings yet
- FitokimiaDocument100 pagesFitokimiaSukmawansyah100% (1)
- OPIOID SEJARAHDocument15 pagesOPIOID SEJARAHAsih Retno WulandhariNo ratings yet
- Biosintesis LignanDocument2 pagesBiosintesis LignanRomdonia Mando SoofiaNo ratings yet
- PARKINSONDocument10 pagesPARKINSONpuputNo ratings yet
- Makalah Farmakoterapi IiDocument18 pagesMakalah Farmakoterapi IimeilaniNo ratings yet
- MEKANISME RESISTENSIDocument8 pagesMEKANISME RESISTENSIindahNo ratings yet
- Laporan Farmakoterapi Syaraf MigrainDocument9 pagesLaporan Farmakoterapi Syaraf MigrainAulia SNo ratings yet
- Laporta Praktikum Farmakologi: Toleransi GlukosaDocument27 pagesLaporta Praktikum Farmakologi: Toleransi GlukosaMalfinr_1267% (3)
- HipertiroidDocument38 pagesHipertiroidHajrahPalembangan100% (1)
- Makalah Farmakoterapi Glaukoma Kelompok 12cDocument26 pagesMakalah Farmakoterapi Glaukoma Kelompok 12cRian NurdianaNo ratings yet
- ANALGETIK NON OPIOIDDocument11 pagesANALGETIK NON OPIOIDSakota BramNo ratings yet
- REVIEW KAPITA SELEKTA SESI UTS GENAP TA 2019/2020Document8 pagesREVIEW KAPITA SELEKTA SESI UTS GENAP TA 2019/2020Rio Pratama YudaNo ratings yet
- Swamedikasi Dan Resep FarmasiDocument59 pagesSwamedikasi Dan Resep FarmasiDian Ulfa Rianda96No ratings yet
- SIMPLIFIKASIDocument12 pagesSIMPLIFIKASIMemey HermanesNo ratings yet
- Alkaloid BelladonaDocument2 pagesAlkaloid BelladonaStefany Grandinata SoesenoNo ratings yet
- Kalsineurin Inhibitor TopicalDocument5 pagesKalsineurin Inhibitor TopicalAnnisa Caul HasanahNo ratings yet
- FenilefrinDocument6 pagesFenilefrinfarid akbarNo ratings yet
- Penggolongan Obat OtonomDocument102 pagesPenggolongan Obat OtonomAqilla FadiaNo ratings yet
- Pedoman Pemilihan Obat Anti Depresan MayaDocument16 pagesPedoman Pemilihan Obat Anti Depresan MayaMammy Nya Allya100% (1)
- Kasus Keracunan NitritDocument6 pagesKasus Keracunan Nitritdebbie sheilaNo ratings yet
- C Fadliah Ramadhan O1a1 18172Document34 pagesC Fadliah Ramadhan O1a1 18172Fadliah RamadhanNo ratings yet
- Makalah Obat-Obat Penurun Kolesterol (Revisi)Document16 pagesMakalah Obat-Obat Penurun Kolesterol (Revisi)vinnavihrNo ratings yet
- OPIOID-ANALGESIKDocument9 pagesOPIOID-ANALGESIKEdward SuryadiNo ratings yet
- Farmakologi DasarDocument17 pagesFarmakologi Dasari gede wiyanaNo ratings yet
- Kimia FarmasiDocument4 pagesKimia FarmasiDrs Ir Mohamad FadelNo ratings yet
- Efek Morfin pada ManusiaDocument18 pagesEfek Morfin pada ManusiaIbnu RahmanNo ratings yet
- Kodein Bedah SyarafDocument17 pagesKodein Bedah SyarafLiuk IrawatiNo ratings yet
- Prosedur PreparatDocument3 pagesProsedur PreparatNita AndriyaniNo ratings yet
- Skin GraftDocument16 pagesSkin GraftNita AndriyaniNo ratings yet
- THT BST OMA Dr. Empu DriantoDocument19 pagesTHT BST OMA Dr. Empu DriantoNita AndriyaniNo ratings yet
- Anatomi TonsilDocument4 pagesAnatomi TonsilNita AndriyaniNo ratings yet
- Definisi, Epidemiologi, Management, Komplikasi, Prognosis Luka BakarDocument25 pagesDefinisi, Epidemiologi, Management, Komplikasi, Prognosis Luka BakarNita Andriyani0% (1)
- Cold AbscessDocument8 pagesCold AbscessNita AndriyaniNo ratings yet
- His Case 3 Li Nita Andriani 10100110128Document16 pagesHis Case 3 Li Nita Andriani 10100110128Nita AndriyaniNo ratings yet
- BHP IimcDocument2 pagesBHP IimcNita AndriyaniNo ratings yet
- Hiponatremia Dan HipernatremiaDocument12 pagesHiponatremia Dan HipernatremiaNita AndriyaniNo ratings yet
- ATLSDocument23 pagesATLSNita Andriyani100% (2)
- Anatomi HandDocument18 pagesAnatomi HandNita AndriyaniNo ratings yet
- ConjunctivitisDocument29 pagesConjunctivitisNita AndriyaniNo ratings yet
- Kelompok 4 - BHP5Document31 pagesKelompok 4 - BHP5Nita AndriyaniNo ratings yet
- OAINSDocument10 pagesOAINSNita AndriyaniNo ratings yet
- MaloklusiDocument5 pagesMaloklusiNita AndriyaniNo ratings yet
- Deviasi Septum NasalDocument4 pagesDeviasi Septum NasalNita AndriyaniNo ratings yet
- Tuberkulosis ParuDocument15 pagesTuberkulosis ParuNita AndriyaniNo ratings yet
- Laporan Case 9 Kelompok e Cleft Lip & PalateDocument111 pagesLaporan Case 9 Kelompok e Cleft Lip & PalateNita AndriyaniNo ratings yet
- Obat Anti TuberkulosisDocument16 pagesObat Anti TuberkulosisNita AndriyaniNo ratings yet
- Resisten GandaDocument3 pagesResisten GandaNita AndriyaniNo ratings yet
- EPISTAKSISDocument14 pagesEPISTAKSISNita AndriyaniNo ratings yet
- KARSINOMA NASOFARING - Definisi-Epidemiologi-PrognosisDocument17 pagesKARSINOMA NASOFARING - Definisi-Epidemiologi-PrognosisNita Andriyani100% (1)
- Tuberculosis Extra PulmonalDocument22 pagesTuberculosis Extra PulmonalNita Andriyani100% (2)
- Plastic Surgery NitaDocument22 pagesPlastic Surgery NitaNita AndriyaniNo ratings yet
- SellulitisDocument8 pagesSellulitisNita AndriyaniNo ratings yet
- Pra Bedah NitaDocument3 pagesPra Bedah NitaNita AndriyaniNo ratings yet
- Dental CariesDocument15 pagesDental CariesNita Andriyani50% (2)
- Flora Normal Di Oral CavityDocument8 pagesFlora Normal Di Oral CavityNita AndriyaniNo ratings yet
- Infeksi OdontogenDocument14 pagesInfeksi OdontogenNita AndriyaniNo ratings yet
- MILIARIADocument24 pagesMILIARIANita AndriyaniNo ratings yet